Mengenal Diatom dalam Kajian Arkeologi Mikroskopik
Tulisan karya : M. Dziyaul F. Arrozain (Arkeologi 2017)
Apa kesan kalian saat membaca kata “mikrofosil” di artikel-artikel arkeologi? Tidak dipungkiri sebagian dari kita telah familiar dengan beberapa jenis mikrofosil, seperti serbuk sari (pollen), pati (starch), dan bahkan fitolit (fitolit). Ketiga hal tersebut memang merupakan mikrofosil yang sering digunakan dalam riset arkeologi. Tapi tahukah kalian, selain ketiga mikrofosil tersebut ternyata juga ada mikrofosil lain yang ikut berperan signifikan dalam riset arkeologi? Iyaa, mikrofosil itu adalah diatom (diatom).
Incoming search terms:
- https://hima fib ugm ac id/mengenal-diatom-dalam-kajian-arkeologi-mikroskopik/ (15)
- diatom (2)
- https://hima fib ugm ac id/mengenal-diatom-dalam-kajian-arkeologi-mikroskopik/#:~:text=Diatom adalah organisme yang hanya – 200 mikrometer (μm) (2)
- https://hima fib ugm ac id/mengenal-diatom-dalam-kajian-arkeologi-mikroskopik/#:~:text=Dalam sistem klasifikasi makhluk hidup laut, cuma ukurannya sangat mini! (1)
- https://hima fib ugm ac id/mengenal-diatom-dalam-kajian-arkeologi-mikroskopik/#:~:text=Diatom centrales memiliki ciri bentuk bentik atau mendiami dasar perairan (1)


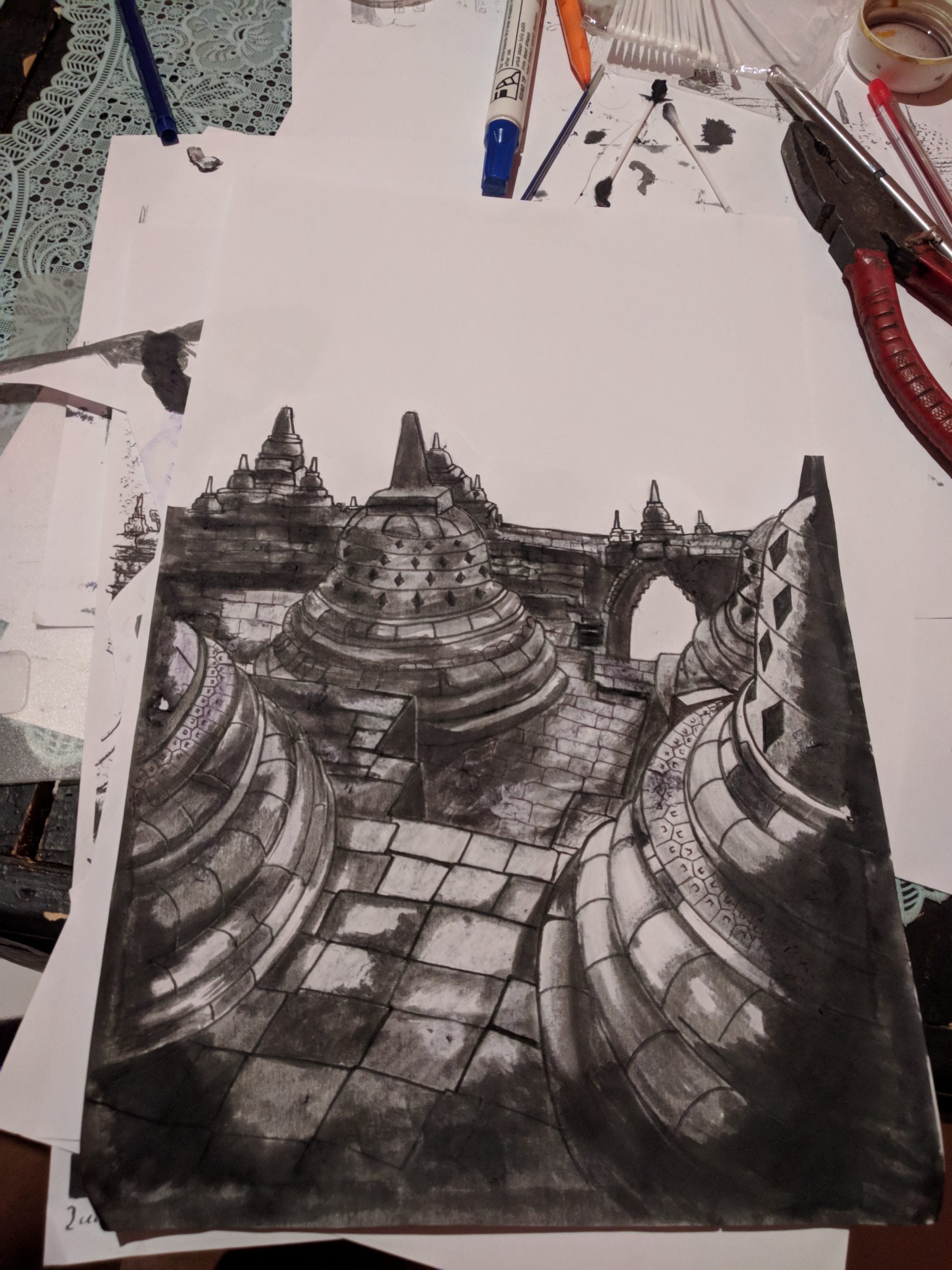



 Halo teman-teman! Ada kabar gembira nih buat mengisi kegiatan saat di rumah aja.
Halo teman-teman! Ada kabar gembira nih buat mengisi kegiatan saat di rumah aja.