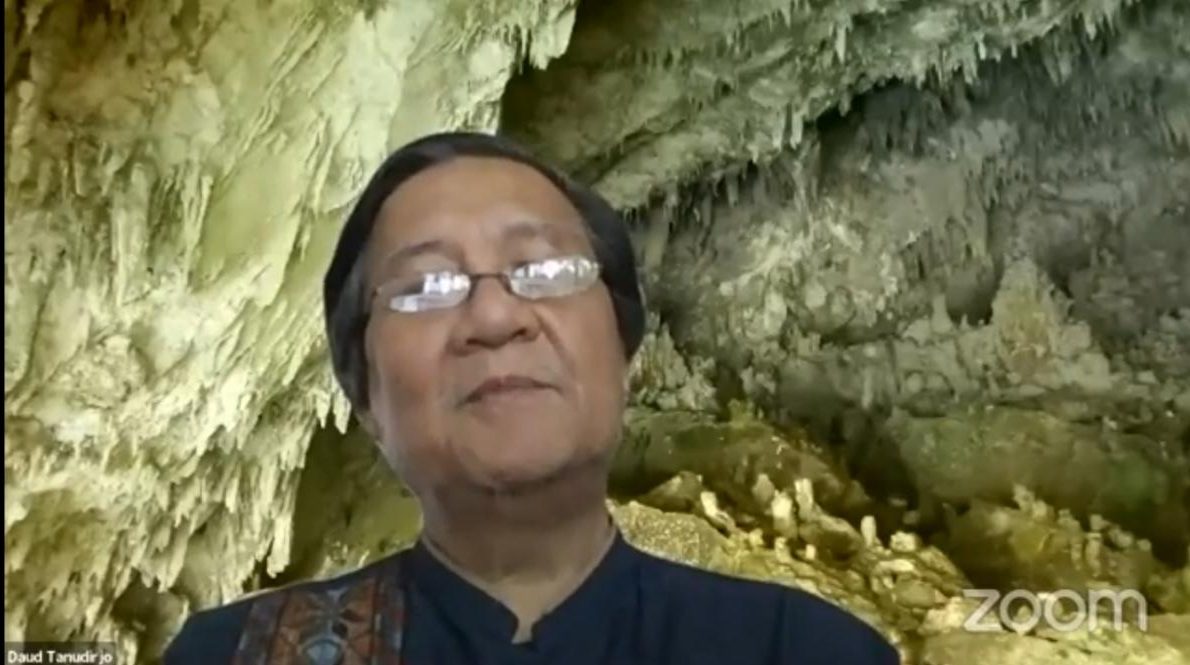
Dalam suatu konsep pengamanan terhadap Warisan Budaya ini dilindungi dari ancaman dan gangguan. Ancaman dan Gangguan ini berbeda arti dan bentuknya. Ancaman merupakan suatu usaha atau kegiatan, yang berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obyek Vital Nasional, sedangkan Gangguan itu sendiri merupakan tindakan nyata yang menimbulkan korban jiwa dan atau harta benda yang dapat merusak psikis seseorang.Dalam menangani hal tersebut dapat dilakukan pengamanan seperti; pencegahan, penangkalan, penanggulangan, dan penegakan hukum.
